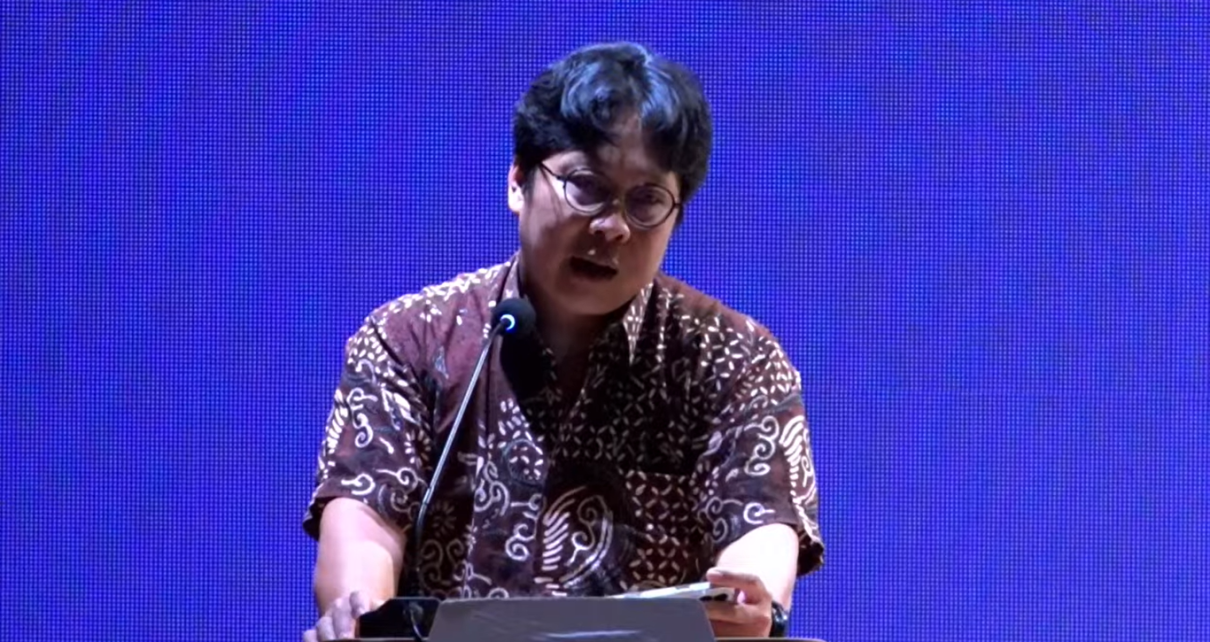Channel9.id, Jakarta – Ledakan inovasi digital dan kecerdasan buatan (AI) yang kian melaju tak hanya mengubah pola belajar, tetapi juga mengguncang fondasi humanisme pendidikan. Hal itu mengemuka dalam Seminar Nasional “Desain Ulang Pendidikan Indonesia: Strategi dan Inovasi Menghadapi Gelombang Disrupsi Digital dan AI” yang diselenggarakan oleh Yayasan Rawamangun Mendidik (YRM) bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Ikatan Alumni UNJ, di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).
Dalam paparannya, Prof Robertus Robet, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta (UNJ), menegaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia selama ini terlalu sering didesain ulang di tingkat administratif—namun justru menambah beban guru dan dosen.
“Setiap ganti pemerintahan, yang didesain itu justru kerjaan guru dan dosen: mengisi aplikasi, melapor, menyesuaikan platform. Sementara esensi perubahan pembelajaran tidak tersentuh,” ujarnya.
Robet menyoroti fakta bahwa teknologi digital berkembang jauh lebih cepat dibanding kemampuan manusia untuk beradaptasi. Akibatnya, ruang belajar yang dulu berbasis dialog kini bergeser ke arah efisiensi, konformitas, dan kalkulasi—seringkali mengabaikan dimensi kemanusiaan.
Ancaman “Manusia yang Usang” di Hadapan Teknologi
Mengutip pemikiran filsuf Jerman Günther Anders, Robet mengingatkan fenomena obsolescence of man—manusia yang merasa kalah, rendah, bahkan tidak memadai di hadapan teknologi yang diciptakannya sendiri.
“Anders sudah memperingatkan jauh hari: teknologi menciptakan mesin yang lebih kuat, lebih presisi, lebih sempurna dari manusia. Secara ironis, manusia menjadi inferior secara sosial, ekonomi, hingga eksistensial,” kata Robet.
Ia mencontohkan situasi di kelas-kelas sekolah elit: siswa membawa gawai terbaru, sementara gurunya merasa “ketinggalan zaman”.
“Guru bisa merasa usang di hadapan siswanya. Ini tekanan ganda yang membuat manusia terdorong bekerja seperti mesin—seragam, terukur, kehilangan jati dirinya,” ucap Robet
Robet juga menyinggung kecenderungan sekolah yang menilai segala sesuatu berdasarkan apa yang bisa diukur. Bahkan program live in yang sejatinya bertujuan memperkaya pengalaman sosial siswa kerap direduksi menjadi sekadar laporan harian dan dokumentasi visual.
“Ketika hanya yang dapat diukur dianggap penting, kita kehilangan kedalaman. Identitas siswa dilihat dari data dan metrik, bukan dari pengalaman manusiawi,” tegasnya.
Menurut Robet, kondisi ini perlu diwaspadai sebagai bentuk teknokratisasi pendidikan—proses di mana logika mesin mengatur perilaku manusia.
Menafsir Ulang Relasi Manusia-Teknologi
Namun Robet tidak berhenti pada sisi gelap digitalisasi. Mengutip pemikiran feminis Donna Haraway, ia menekankan bahwa manusia modern pada dasarnya adalah “cyborg”—makhluk yang tak terpisahkan dari teknologi.
“Batas antara manusia dan mesin semakin kabur. Kita tidak mungkin lepas dari ponsel kita. Karena itu, relasi ini harus dipahami bukan sebagai ancaman, tapi peluang untuk memperluas imajinasi dan kolaborasi,” jelasnya.
Menurut Haraway yang dikutip Robet, pendekatan cyborg justru menolak batas-batas kaku, mendorong kolaborasi, dan memperluas kreativitas.
Robet menegaskan bahwa pendidikan digital bukanlah takdir, melainkan arena pertarungan politis—siapa yang memegang kendali: manusia atau teknologi?
Ia mengusulkan tiga langkah kunci: pertama, mengembalikan marwah manusia. Pendidikan harus menjaga subjektivitas manusia, bukan menjadikannya sekadar roda dalam mesin birokrasi dan platform digital. Kedua, mendorong subjek cyborg yang kritis. Guru dan siswa bukan menolak teknologi, tetapi memanfaatkannya secara kritis—memahami bias algoritma, relasi kuasa digital, dan mengontrol arah penggunaan teknologi.
Ketiga, mengembangkan pedagogi hibrida. Proses belajar harus menggabungkan keunggulan teknologi dengan pengalaman manusiawi yang tak tergantikan.
“Tujuan pendidikan bukan abstrak. Tugas kita merakit diri di tengah dunia digital—di saat yang sama merawat relasi kita dengan teknologi dan dengan alam,” ujarnya.
Robet menutup paparannya dengan penekanan bahwa literasi digital tidak boleh berhenti pada kemampuan menggunakan aplikasi atau platform.
“Kita harus memahami logika teknologi, bias algoritma, relasi kuasa di baliknya. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi pengguna pasif, bukan pembentuk masa depan,” tegas pengajar bergelar Doktor Filsafat di STF Driyakara ini.