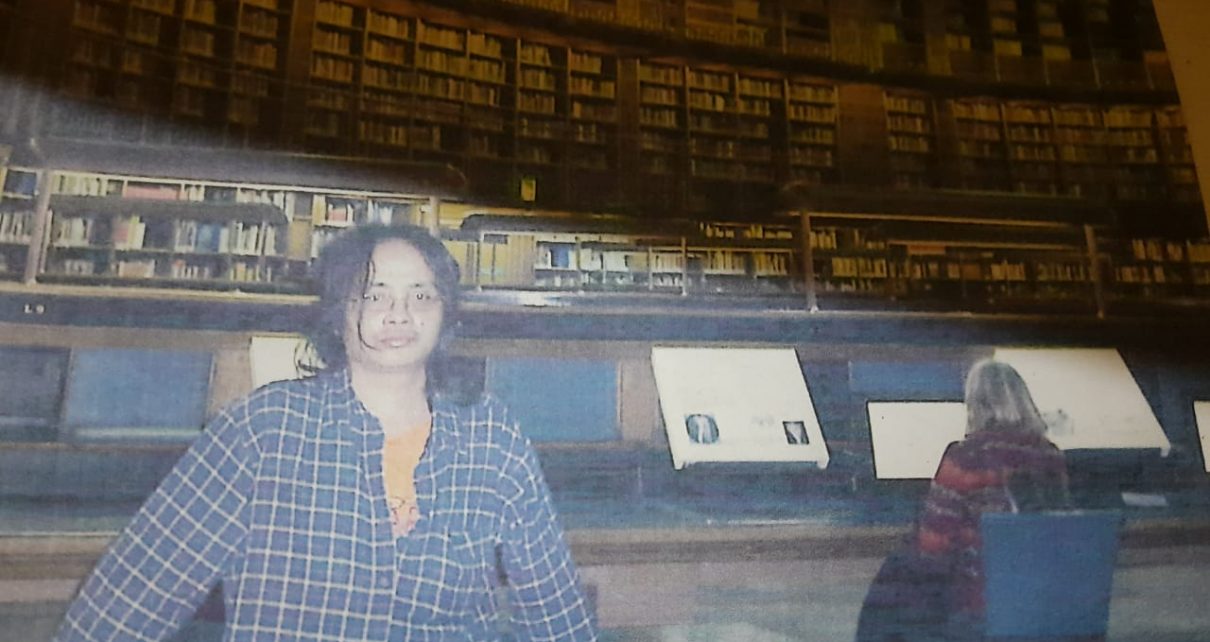Oleh: Soffa Ihsan
Channel9.id – Jakarta. Hari-hari ini dunia keberagamaan kita tengah terhantam oleh tsunami faham-faham puritan dan ekstrem. Ada postulasi yang kerap dilontarkan bahwa terorisme selalu lahir dari benih’ puritan. Ada rumusan; eksklusif, puritan, intoleran dan teroris. Tidaklah berlebihan, memang ada banyak fakta di lapangan menunjukkan rentetan itu.
Diantara yang menarik adalah serangan terhadap konsep wali. Di era erupsi digital saat ini, mudah kita saksikan di medsos betapa banyak ustadz-ustadz puritan yang dengan lantang menolak adanya kewalian. Kewalian dituduh takhayul diperkeruh dengan ungkapan tabdi, tasyrik dan juga takfir. Apa yang bisa dicermati dari kisruh ini adalah keberagamaan menjadi sangat kering kerontang tanpa pendalaman atau penghayatan yang ekstasis. Beragama hanya ibarat olah tubuh tanpa olah rasa. Padahal sejatinya beragama sudah seyogyanya menukik dan menembus kedirian terdalam untuk bersesambung dengan kekuatan adikodrati yaitu Allah SWT. Tanpa perembesan ruhaniyah ini, maka beragama sekedar kulit atau verbalis dan rentan terpelanting dalam kehampaan hingga bisa berakibat pada terbentuknya pikiran, sikap dan tindakan kaku, keras dan jumud (tathorruf dan syiddatut tanathu). Cilakanya, pengajaran agama saat ini tumbuh dari kerangkeng puritanisasi ini yang lalu diviralisasi. Tak sedikit masyarakat berbagai lapis termasuk generasi milenial dan Gen Z menerimanya tanpa memamah dan berujung pada militansi beragama yang sering tak terkendali.
Apa itu Kewalian?
Wali dari segi bahasa berasal dari kata al-wala yang artinya dekat (al-qarb). Secara umum (ammah), setiap mukmin adalah waliyullah. Seorang hamba mukmin akan senantiasa mendapatkan pertolongan dan pemeliharaan dari Allah. Dan ini diisyaratkan dalam surah al-Baqarah ayat 257 yang berbunyi “Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman”. Dalam surah al-Araf juga dinyatakan “Dia menjadi wali bagi orang-orang saleh”. Dalam surah al-Baqarah ayat 286 dikatakan “Engkau adalah wali kami, maka kurniakanlah kami kemenangan atas orang-orang kafir”. Dalam surah Muhammad ayat 11 dinyatakan “Yang demikian itu adalah karena Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang kafir tidak ada wali bagi mereka”. Dan dalam surah al-Maidah ayat 55 dikatakan “Sesungguhnya wali kamu adalah Allah dan Rasul-Nya”.
Baca juga: Muharam dan Hijrah Nusantara
Ibnu Katsir menafsirkan bahwa para wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapa saja yang bertakwa, maka dia adalah wali Allah (Lihat: Tafsir Ibnu Katsir, juz 2)
Makna istilah wali memang luas. Intinya adalah hubungan yang amat dekat. Allah adalah wali dari seluruh hamba dan makhluk-Nya, karena Dia berkuasa lagi Maha Tinggi. Dan kuasa-Nya itu adalah langsung. Si makhluk wajib berusaha agar dia pun menjadi wali pula dari Allah. Kalau Allah sudah nyata tegas dekat kepadanya, diapun hendaklah ber-taqarrub, artinya mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka akan timbullah hubungan perwalian yang timbal balik.
Dalam maqam spiritual, wali dalam artian khusus (khas) merujuk pada mereka yang telah melebur dirinya ke haribaan Allah (fana al-abdi fi al-haq) serta kekal bersama Allah (baqauhu bihi).
Ibnu Abbas seperti tercatat dalam tafsir Al-Khazin menyatakan bahwa wali-wali Allah itu adalah ‘orang yang mengingat Allah dalam melihat’. Imam Thabari meriwayatkan dari Said bin Zubair berkata bahwa Rasulullah telah ditanya tentang wali-wali Allah. Baginda mengatakan “Mereka itu adalah orang yang apabila melihat, mereka melihat Allah”.
Imam Ghazali menyebutkan bahwa “Allah pernah memberi ilham kepada para shiddiq. “Sesungguhnya ada hamba-hamba-Ku yang mencintai-Ku dan selalu merindukan Aku dan Akupun demikian. Mereka suka mengingati-Ku dan memandang-Ku dan Akupun demikian. Jika engkau menempuh jalan mereka, maka Aku mencintaimu. Sebaliknya, jika engkau berpaling dari jalan mereka, maka Aku murka kepadamu.” Tanya seorang siddiq,”Ya Allah, apa tanda-tanda mereka?” Firman Allah,”Di siang hari, mereka selalu menaungi diri mereka, seperti seorang pengembala yang menaungi kambingnya dengan penuh kasih sayang, mereka merindukan terbenamnya matahari, seperti burung merindukan sarangnya. Jika malam hari telah tiba tempat tidur telah diisi oleh orang-orang yang tidur dan setiap kekasih telah bercinta dengan kekasihnya, maka mereka berdiri tegak dalam shalatnya. Mereka merendahkan dahi-dahi mereka ketika bersujud, mereka bermunajat, menjerit, menangis, mengadu dan memohon kepada-Ku. Mereka berdiri, duduk, rukuk dan sujud untuk-Ku. Mereka rindu dengan kasih sayang-Ku. Mereka Aku beri tiga karunia. Pertama, mereka Aku beri cahaya-Ku di dalam hati mereka, sehingga mereka dapat menyampaikan ajaran-Ku kepada manusia. Kedua, andaikata langit dan bumi dan seluruh isinya ditimbang dengan mereka, maka mereka lebih unggul dari keduanya. Ketiga, Aku hadapkan wajah-Ku kepada mereka. Kiranya engkau akan tahu, apa yang akan Aku berikan kepada mereka?” (Lihat: Ihya Ulumuddin, juz 1 dan juz IV)
Wali Di Mata Sufi
Hakim Tirmidzi, seorang sufi dari Uzbekistan, mendefinisikan wali Allah adalah seorang yang demikian kokoh di dalam peringkat kedekatannya kepada Allah (fi martabtih), memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu seperti bersikap shidq (jujur dan benar) dalam perilakunya, sabar dalam ketaatan kepada Allah, menunaikan segala kewajiban, menjaga hukum dan perundang-undangan (al-hudud) Allah dan mempertahankan posisi kedekatannya kepada Allah (al-qurbah). Dalam keadaan ini, menurutnya, seorang wali mengalami kenaikan (taraqqi) peringkat sehingga berada pada posisi yang demikian dekat dengan Allah, kemudian ia berada di hadapan-Nya dan menyibukkan diri dengan Allah sehingga lupa dari segala sesuatu selain Allah. Karena kedekatannya dengan Allah, seorang wali memperoleh ishmah (pemeliharaan) dan karamah (kemuliaan) dari Allah.
Ada lagi istilah karamah al-awliya yang berarti kemuliaan, kehormatan (al-ikram), penghargaan (al-taqdir); dan persahabatan (al-wala) yang dimiliki para wali Allah berkat penghargaan, kecintaan dan pertolongan Allah kepada mereka. Karamah al-awliya itu merupakan salah satu ciri para wali secara lahiriah (alamat al-awliya fi al-zhahir) yang juga dinamakannya al-ayat atau tanda-tanda.
Orang yang menolak karamah al-awliya, menurut Hakim Tirmidzi, disebabkan mereka tidak mengetahui persoalan ini kecuali kulitnya saja. Mereka tidak mengetahui perlakuan Allah terhadap para wali. Sekiranya orang tersebut mengetahui hal ihwal para wali dan perlakuan Allah terhadap mereka, niscaya mereka tidak akan menolaknya. Penolakan mereka terhadap karamah al-awliya, menurut at-Tirmidzi, disebabkan oleh kadar akses mereka terhadap Allah hanya sebatas menegaskan-Nya, bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan kejujuran (al-shidq), bersikap benar dalam mewujudkan kesungguhan sehingga meraih posisi al-qurbah (dekat dengan Allah). Sementara, mereka buta terhadap karunia dan akses Allah kepada hamba-hamba pilihan-Nya. Demikian juga, buta terhadap cinta (mahabbah) dan kelembutan (rafah) Allah kepada para wali. Apabila mereka mendengar sedikit tentang hal ini, mereka bingung dan menolaknya.
Adapun derajat kewalian, dalam pandangan Tirmidzi dapat diraih dengan terpadunya dua aspek penting, yakni karsa Allah kepada seorang hamba dan kesungguhan pengabdian seorang kepada Allah. Aspek pertama merupakan wewenang Allah secara mutlak; sedangkan aspek kedua merupakan perjuangan seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah.
Ada dua jalur yang biasa ditempuh oleh seorang sufi guna meraih derajat kewalian. Jalur pertama disebut thariqah al-minnah (jalan golongan yang mendapat anugerah), sedangkan jalur kedua disebut thariq ashhab al-shidq (jalan golongan yang benar dalam beribadah). Melalui jalur pertama, seorang sufi meraih derajat kewalian di hadapan Allah semata-mata karena karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikendaki Allah di antara hamba-hamba-Nya. Sedangkan melalui jalur kedua, seorang sufi meraih derajat kewalian berkat keikhlasan dan kesungguhannya di dalam beribadah kepada Allah. Seseorang yang meraih derajat kewalian melalui jalur kedua disebut wali haqq Allah. Derajat kewalian yang diraih melalui jalur kedua ini diperoleh setelah seorang sufi bertaubat dari segala dosa dan bertekad bulat untuk membuktikan sesungguhan taubatnya dengan konsisten dalam menunaikan segala yang diwajibkan, menjaga al-hudud (hukum dan perundang-undangan Allah) dan mengurangi al-mubahat (hal-hal yang dibolehkan); kemudian memperhatikan aspek batin dan menjaga kesuciannya dengan seksama. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan mereka tidak bersedih.(Q.S. Yunus: 62).
Abu Yazid al-Busthami memperkenalkan konsep al-wali al-kamil (wali yang sempurna). Menurutnya, wali yang sempurna ialah orang yang telah mencapai marifah yang sempurna tentang Tuhan, ia telah terbakar oleh api Tuhannya. Marifah yang sempurna akan membawa seorang wali fana dalam sifat-sifat ketuhanan. Wali yang fana dalam nama Allah, al-zhahir (yang nyata), akan dapat menyaksikan qudrah Tuhan. Wali yang fana dalam nama-Nya, al-bathin (yang tersembunyi) akan dapat menyaksikan rahasia-rahasia alam. Wali yang fana dalam nama-Nya, al-akhir (yang akhir), akan menyaksikan masa depan.
Ibnu Arabi menghubungkan konsepsi al-awliya dengan kemampuan menangkap al-athaya (pemberian dan anugerah) Allah. Menurut Ibnu Arabi, ada dua jenis al-athaya (pemberian), yakni yang bersifat dzatiyyah dan yang bersifat asmaiyyah. Adapun al-athaya al-dzatiyyah tidak terjadi kecuali melalui tajalli ilahi Sedangkan tajalli merupakan pengetahuan tertinggi tentang Tuhan. Pengetahuan ini tidak diberikan kecuali kepada khatam al-rusul (pamungkas para utusan) dan khatam al-awliya (pamungkas para wali).
Bagaimana keberadaan para wali yang ada di Nusantara? Selama ini tersembunyi ditengah popularitas Wali Sanga. Ternyata di Nusantara ini berderet para wali yang berjuang demi syiarnya Islam dengan penuh kasih mendampingi masyarakat untuk bisa menikmati keindahan ajaran Islam. Para wali tersebut jelas tidak bersikap intoleran, radikal, atau bahkan teroris dalam menyebarkan ajaran Islam. Sebaliknya mereka bertindak secara bijak bestari, penuh toleransi dan persaudaraan (alhanafiah al-samhah). Dan pula para wali ini telah menebar kedamaian, mengajak berfikir dan beragama secara mendalam, dan bertindak moderat dengan mengenyahkan segala rupa radikalisme.
Kita bisa deret para sufi-wali Nusantara seperti Syeikh Ahmad Khatib Sambasi, Syeikh Kemas Fakir al-Din, Syeikh Abdus Samad al-Palimbani, Syeikh Burhanuddin Ulakan, Syeikh Syamsuddin al-Sumatrani, Syeikh Yusuf al-Makassari, Syeikh Sholeh Darat, Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari, Syeikh Nuruddin Arraniri, Syeik Muhammad Arsyad al-Banjari, Syeikh Abdurrauf al-Singkili, Syeikh Muhammad Asád al-Bugisi, atau Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari. Banyak khazanah wali yang adiluhung di negeri kita bahkan hingga masa kontemporer seperti Mbah Mutamakin Pati, Kyai Hamid Pasuruan, Mbah Lim Klaten, Gus Mik Kediri, Habib Sehan, Gus Jakfar dan lainnya. Banyak pula wali mastur yang menyembunyikan diri dari tatapan mata khalayak. Tipe wali ini bergerilya senantiasa menebar kebaikan dan kedamaian di tengah masyarakat tanpa puja puji dan imun dari cacimaki (la yakhofuna laumata laim). Para wali inilah sosok-sosok yang majdzub dan kerap khoriq al-adat diluar nalar lazim, tetapi satu komitmen yaitu perilakunya menyejukkan, tebar cinta kasih, mencintai negeri serta menolak sikap serta aksi ekstrim dan radikal.
Sontak, kita kembali membayangkan, andaikan di bumi pertiwi ini dulu tidak mendapatkan dakwah model wali tersebut dan sebaliknya yang berkiprah justru mereka yang berpandangan puritan dan radikal, bagaimana jadinya Indonesia sekarang? Apakah kita masih bisa menyaksikan Indonesia dihuni oleh mayoritas muslim?
Walhasil, dengan mengkaji kewalian rasanya kita bisa membelalakkan mata betapa kedalaman spiritualitas menjadi niscaya. Ia bagaikan menapaki labirin yang lembut berliku. Beragama tak hanya mampu diolah melalui lahiriah. Laku lahiriah sebagai titian untuk menuju kehakikian keilahiaan.
Disamping itu, menginsyafi adanya dunia spiritualitas kewalian akan menjadikannya sebagai cermin ditengah-tengah situasi sekarang yang banyak orang menyebut telah terjadi conservative turn yang seringkali terjadi pembajakan nilai-nilai keislaman yang adiluhur. Agama kerap dijadikan sebagai perisai dan peledak untuk tindakan kekerasan dan anti kemanusiaan.
Tak ayal, dunia yang seperti ini akan semakin membarakan untuk kembali menengok kedirian kita melalui peneladanan terhadap para sosok-sosok wali. Inilah segebung hikmah menelisik kewalian. Karena itu, Iqra! Niscaya kita akan bisa menyesap “mutiara manikam” yang sangat lembut (lathaif) sebagai anugerah Allah untuk kedamaian di bumi pertiwi dan semesta.
Penulis adalah Peneliti dan Marbot Rumah Daulat Buku (Rudalku)