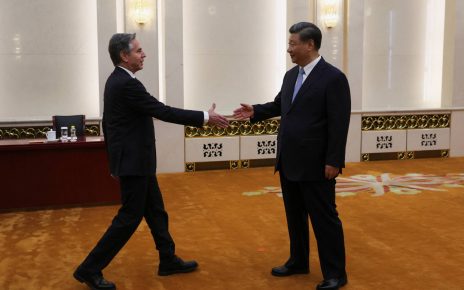Channel9.id-Kuala Lumpur. Di tengah gemuruh kekuasaan menara beton, kaca, dan baja Kuala Lumpur yang memantulkan cahaya lampu kota, sepetak tradisi mencoba bertahan hidup. Kampong Bharu, yang terletak di tengah pusat kota, membentengi diri dengan rumah panggung kayu rendah, berpagar seadanya, dan rerumputan yang menyelinap dari celah beton.
Penelusuran ke kawasan ini dilakukan di sela-sela pertunjukan Wayang Santri oleh Dalang Ki Haryo Susilo Entus Susmono pada 26 dan 27 Juli 2025 di ibukota Malaysia itu. Pementasan itu juga simbol pertemuan tradisi di ruang publik modern. Pertunjukan ini memadukan budaya dharmasastra dan santri dalam harmoni lintas batas di salah satu kota paling modern di Asia Tenggara. Paduan dari kontras semacam itu juga yang tergambarkan dari Kampong Bharu.
Jalan-jalan sempit seperti Jalan Raja Muda Abdul Aziz dan Lorong Raja Muda Musa seakan menjadi lorong waktu. Tidak ada gerbang, tapi terasa jelas batas antara dua dunia. Kuala Lumpur yang modern dan mengilap dan kampung tua dengan rumah bercat mengelupas, papan nama toko-toko kecil, dan pekarangan yang ditumbuhi pohon rindang, pohon pisang, serta rumput yang sebagian besar mengering tak terurus. Beberapa rumah memasang bendera Malaysia di dinding depannya.
Setiap pagi, suasana kampung ini selalu bermula dengan aroma nasi lemak, satai, dan bunyi kopitiam membuka gerai. Warga menyapa dengan bahasa Melayu yang kental. Begitupun dengan Minggu pagi ini (27/7/2025), ramai warga setempat dan pendatang memenuhi kedai makan. Satu porsi nasi lemak, dengan lauk paru balado, telur rebus dan dadar, ditambah mie goreng dan sambal dibanderol 11 RM atau sekitar Rp 42.350 (kurs Rp.3.850 per hari ini – red). Satu porsi nasi yang cukup besar untuk ukuran sarapan pagi. Satu tea O atau teh tawar panas seharga RM 2 atau sekitar Rp.7.700.
Di kedai sebelah, sekumpulan laki-laki dewasa memenuhi kedai kopi. Riuh percakapan di antara mereka dengan Bahasa Melayu, sambil menyeruput kopi. Semua aroma dan dengung suara menciptakan suasana bahwa seolah-olah Kuala Lumpur belum pernah berubah sejak 1960-an.
Siang menjelang, warung-warung menjual laksa dan nasi kerabu. Hidangan Kelantan menjadi magnet lokal maupun turis asing yang ingin merasakan masakan otentik Melayu. Seakan, makanan adalah bahasa peradaban yang terus dipelihara.
Kerumunan lalu terjadi secara spontan. Lajur pejalan kaki mendadak berubah menjadi pasar kecil ketika malam tiba. Penjual makanan kaki lima mendirikan lapak mereka di jalan.
Semua tampak begitu harmoni, kendati, kenyataannya, perubahan terus mengintai. Kampong Bharu bukan cuma pemukiman—ia adalah pernyataan identitas. Sejak didirikan pada tahun 1899 oleh Sultan Selangor sebagai Malay Agricultural Settlement, kawasan ini dimaksudkan untuk memberi ruang bagi kaum Melayu bertani di dalam kota yang kala itu mulai didominasi imigran Cina dan India.

Kampong Bharu lalu tumbuh menjadi simbol keberadaan Melayu urban di tengah kolonialisme dan kemudian modernisasi. Pada dekade 1950-an, tempat ini menjadi area eksklusif etnis Melayu, dan berkembang sebagai ruang politik prokemerdekaan, Di sinilah akar-akar gerakan nasionalisme Melayu tumbuh, dan kelak menjadi lahan subur bagi tumbuhnya organisasi-organisasi seperti UMNO. Peristiwa kelam kerusuhan 13 Mei 1969 juga terjadi di batas wilayah kampung ini. Kemelut itu menjadi catatan bahwa identitas etnik dan politik pernah menjadi faktor kesadaran kolektif di sana.
Yang terlambat mereka sadari adalah tanah di Kampong Bharu—yang dahulu dianggap terlalu pinggir untuk dilirik pemodal—lalu menjadi rebutan karena lokasinya yang hanya selemparan batu dari pusat bisnis Kuala Lumpur. Hanya dua kilometer dari KLCC.
Sejak era 1970-an, berbagai rencana modernisasi diajukan. Pemerintah kota dan federal berlomba-lomba menawarkan skema pembangunan: dari apartemen vertikal, kompleks perkantoran, hingga kawasan mixed-use. Tekanan modernisasi kian meningkat pada tahun 1980-an ketika harga tanah melambung dan sekarang menyentuh RM 50 ribu (sekitar Rp 200 juta) per meter persegi.
Tapi semua rencana pembangunan tak kunjung tuntas karena sifat kepemilikan tanah yang fragmented: satu plot sering diwariskan ke puluhan ahli waris, menciptakan kebuntuan konsolidasi. Dan lebih dari itu, warga yang tinggal di sana mempertahankan nilai hidup yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sebidang tanah bisa diwarisi hingga puluhan orang.
Kudis dan Bonus dari Asia Tenggara
Kontroversi lalu memuncak ketika mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyebut Kampong Bharu sebagai “kudis” yang perlu dibersihkan dan dibangun ulang. Pernyataan tersebut menjadi pemicu resistensi budaya yang kuat dari warga dan aktivis pelestarian. Pemerintah kemudian membentuk Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu (PPKB) dengan Pelan Induk 2040 yang menjanjikan pembangunan modern berbasis identitas, namun pelaksanaannya masih jauh dari kepastian.
Tawaran kompensasi finansial tinggi kepada pemilik lahan gagal menghentikan kekhawatiran bahwa kehilangan rumah berarti kehilangan sejarah Roslan, pemilik kedai kopi tarik di Jalan Raja Abdullah, menggambarkan pandangan warga setempat: “Tanah ini bukan harta, tapi warisan. Kalau diganti apartemen, kami tak punya tempat kembali,” katanya.
Salem, anak muda Kampong Bharu, mempertegas. Pembangunan boleh diterima, tapi identitas dan kepemilikan harus tetap milik Melayu. Warga harus dilibatkan dalam proses perencanaan agar tidak sekadar dijadikan objek pembangunan. “Kami bukan antipembangunan. Bangunlah sesuai cara kami. Pertahankan arsitektur kampung, dan jangan lepaskan tanah dari orang Melayu,” ujarnya.
Ahmad Murad Merican, pakar warisan budaya dari International Islamic University Malaysia, menegaskan bahwa nilai Kampong Bharu terletak pada komunitas yang masih hidup, bukan sekadar fisik bangunan. Ia menyatakan, kampung Bharu adalah warisan hidup. Bukan artefak museum, tapi ruang budaya yang masih bernapas.
Laporan London School of Economics (LSE) pada 2023 memasukkan kampung ini sebagai model perlawanan terhadap gentrifikasi—bentuk keteguhan sosial di tengah tekanan kapital kota. LSE menyebut kawasan ini simbol “resistance of spatial dispossession” alias perlawanan terhadap kehilangan ruang oleh kaum marjinal kota. Nilai estetika arsitektur dan tata ruang Kampong Bharu mereka sebut sebagai bonus yang jarang ditemukan di kota modern Asia Tenggara.
Pengamat internasional seperti Amanda Achmadi dari University of Melbourne menyampaikan bahwa fenomena urban di kota-kota Asia sering menghapus nilai-nilai memori sosial. Namun di Kampong Bharu, garis antara ruang publik dan privat kabur. Jalan bisa berubah menjadi aula keluarga saat festival, mencerminkan nilai sosial urban yang khas di Asia Tenggara.
Meskipun turis asing kerap datang untuk foto safari di rumah kayu dengan latar gedung tinggi, dan mencicipi makan lokal, pemerintah belum bersedia mencalonkan Kampong Bharu sebagai situs UNESCO. Ketua lembaga warisan nasional dan Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan status ini akan menghambat fleksibilitas pembangunan. Pemerintah sepertinya tetap berniat mepermak habis lanskap tradisi ini.
Para pengembang juga tidak tinggal diam. Proposal demi proposal disusun dan tekanan terhadap warga perlahan meningkat. Bukan dengan penggusuran paksa, tetapi dengan bujukan bertubi-tubi, disertai janji apartemen baru dan kompensasi besar. Tapi warga belajar dari kampung-kampung lain yang sudah berubah wajah: begitu tanah dilepas, biaya hidup naik, dan mereka terusir dari kota mereka sendiri.
Begitulah, Kampong Bharu bukan sekadar nostalgia. Lahan itu adalah cermin konflik abadi antara tradisi dan modernitas, antara warisan dan ekonomi, antara suara rakyat dan rencana negara. Lampu kota dari sela Menara TRX menerpa pucuk daun pisang yang tumbuh di halaman rumah. Dinding kayu terlihat lusuh dengan kaligrafi Islami di atas pintu.
Kampong Bharu adalah pengingat paling lantang bahwa tidak semua yang lama harus dikubur. Dalam emporium modernitas dan pembangunan yang mengebu-gebu, Kampong Bharu adalah ruang bagi tradisi dan masyarakat untuk tetap bernafas. Di tengah gempita Kuala Lumpur yang memburu masa depan, ada sepetak lahan yang bertahan dan menolak tenggelam, menolak dilupakan. Sepetak Melayu di tengah megapolitan yang memilih tetap menjadi dirinya sendiri.
Baca juga: Ketika Jerebu Kembali Selimuti Kuala Lumpur